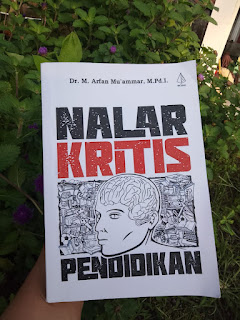 |
| "Kekerasan simbolik dilakukan dengan mekanisme “penyembunyian kekerasan” menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian.” - Pierre Bourdieu - |
Buku
“Nalar Kritis Pendidikan” ditulis oleh M. Arfan Mu’ammar, seorang dosen di
Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sampul depan buku ini ada gambar wajah
manusia dengan bagian kepala dibuat transparan sehingga otak di dalamnya
terlihat. Gambar ini sesuai sekali dengan judul buku. Nalar kritis tentu erat
kaitannya dengan otak yang merupakan sarana berpikir kritis. Kalau otak tidak
beres bagaimana mau berpikir kritis?
Bagian
latar belakang gambar wajah manusia itu adalah benda-benda yang erat kaitannya
dengan pendidikan. Banyak sekali. Pulpen, pensil, bola, gitar, buku, kok, tas
sekolah, mesin ketik, kuas, cat, dan telepon pintar. Benda-benda ini boleh jadi
melambangkan betapa pendidikan itu kompleks sekali. Ia tak semata-mata mengurus
perihal kecerdasan otak. Ia juga mengurus kelembutan perasaan yang diperoleh
melalui seni, dilambangkan dengan kuas dan cat.
Pendidikan
juga berurusan dengan kesehatan para peserta didik, dilambangkan dengan bola
dan kok. Ada pula telepon pintar yang melambangkan budaya kita saat ini.
Memang
begitu kompleksnya pendidikan
karena ia mengurus hampir semua aspek dalam kehidupan ini. Pendidikan
diharapkan mampu menghapus kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diharapkan
mampu menumbuhkan jiwa nasionalis. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan
orang-orang yang agamis. Begitu kompleks. Tak heran jika masalah yang berkaitan
dengan pendidikan juga tentulah sangat kompleks. Ruwet.
Bagian
pertama buku ini membahas teori-teori pendidikan seperti behaviorisme,
kognitifisme, humanisme, konstruktivisme, dan teori sibernetik. Kalau Anda
seorang guru tentu sudah tak asing dengan teori-teori ini. Ada baiknya langsung
dilompati saja. M. Arfan hanya membahasnya secara sekilas saja.
Bagian
kedua buku ini mulai membahas permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Judul-judul
tulisan di bagian kedua buku ini diantaranya: “Calistung: Kapan Diajarkan?”,
“Jangan Silau dengan Prestasi Sekolah!”, “Kelas Kompetisi atau Kelas Inklusi?”,
“Standarisasi Pendidikan: Perlukah?”, “Dilema Evaluasi Pembelajaran”,
“Demitologisasi Profesi Guru”, “Sekolah Kawasan dan Pemerataan Pendidikan”,
:Full Day School: Perlukah?”, dan “Mengeringnya Nalar-Literasi
dan Menyuburnya Industri Hoax”.
Apa yang dibahas dalam bagian kedua buku ini
sebenarnya telah sering dibahas di media sosial, bahkan menjadi perdebatan
hangat di antara warganet. Kita bisa dengan mudah menemukan di media sosial
perdebatan hangat tentang sejak kapan sebaiknya calistung diajarkan. Berbalas
argumen antara warganet seperti pertandingan tinju saja. Warganet saling
menyerang. Kadang diselingi curhat-curhat tentang pengalaman menyekolahkan
anaknya, bahkan hingga pengalaman mereka sendiri. Kita harus pandai menangkap
ide-ide yang berlesatan di sana dan memilahnya. Beda dengan di buku ini,
pembahasan mengenai kapan sebaiknya calistung diajarkan disajikan dengan runut,
sistematis. Memang begitulah yang diharapkan dari buku yang ditulis oleh
seorang dosen.
Pembahasan di buku ini juga kerap diwarnai dengan referensi
dari berbagai buku. Saat mengurai permasalahan mengenai kapan sebaiknya
calistung diajarkan, M. Arfan mengutip buku berjudul Hypnoteaching and
Hypnotheraphy for Brilliant Kids karya Dr. Taufiqi. Di pembahasan ini kita
juga akan bertemu dengan nama-nama seperti Maria Montessory, Fredick Frobel,
Piaget, Debby D Porter, Colin Rose, hingga Malcom J Nicholl. M. Arfan
menyarankan orang tua untuk pandai-pandai memilih apakah akan mengajarkan
calistung pada anak pada usia 1 – 6 tahun atau 7 – 12 tahun. Keduanya memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Di bagian kedua buku ini M. Arfan juga membahas
kecenderungan masyarakat kita yang bangga jika anaknya masuk sekolah favorit
yang punya segudang prestasi. Padahal di balik prestasi yang segudang itu ada
“eksploitasi” yang tersamarkan. Sekolah favorit biasanya hanya menerima
siswa-siswa yang pintar-pintar saja. Dengan kata lain, inputnya memang bagus.
Tinggal poles sedikit saja jadilah siswa gemilang yang mampu menjuarai berbagai
lomba. Sekolah lantas mengklaim telah berhasil. Artinya, belum tentu sekolahnya
yang bagus. Jika hanya diberi anak-anak yang sering disebut “buangan” apakah
sekolah favorit akan tetap mampu berprestasi? Orang tua mungkin melupakan hal
ini.
M. Arfan kemudian menunjukkan bagaimana cara
menentukan apakah sebuah sekolah memang benar-benar bagus atau hanya karena
input siswanya saja yang bagus. Ia menggunakan apa yang disebut dengan indeks
produktivitas. Ia menuliskan contoh cara menghitungnya hingga jika kita
mengikuti caranya, kita akan dapat membandingkan dua sekolah untuk melihat mana
yang lebih berkualitas. Caranya mudah. Hitungannya sederhana. Kukira pembahasannya
mengenai indeks produktivitas menjadi pengingat agar orang tua tak mudah
terjebak kemilau piala yang dipajang di lobi-lobi sekolah.
Bagian ketiga buku ini membicarakan
persoalan-persoalan sosiologis dalam pendidikan. Judul-judul artikel dalam
bagian ketiga ini antara lain: “Pendidikan dan Ketertiban Sosial”, “Kesadaran
Kolektif”, “Kekerasan Simbolik di Sekolah”, “Homeschooling dan Kepekaan
Sosial”, “Teaching is Touching”, Sekolah Elite Belum Tentu Bermutu”, “Kebodohan
dan Kemiskinan”, “Profetik Consciousness (Kesadaran Kenabian)”, dan “Satu Rumah,
Satu Sarjana”.
Yang menarik di bagian ini menurutku adalah artikel
dengan judul “Kekerasan Simbolik di Sekolah”. Artikel ini membahas kekerasan
simbolik di dunia pendidikan. Kekerasan simbolik atau symbolic violence dipopulerkan
oleh Pierre Bourdieu, seorang sosiolog dari Prancis. Pierre Bourdieu
mengungkapkan bahwa kekerasan simbolik dilakukan dengan mekanisme “penyembunyian
kekerasan” menjadi sesuatu yang diterima
sebagai “yang memang seharusnya demikian”.
Di artikel ini, kekerasan simbolik yang dibahas adalah
yang tersembunyi dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE). Dalam salah satu buku, “pekerjaan
ayah” selalu disimbolkan dengan pekerjaan kantoran, disertai gambar seorang
ayah yang memakai dasi, bersepatu, dan membawa koper. Lalu, di mana anak
petani, anak tukang becak, atau anak pemulung berada? Gambar tukang becak
misalnya, tidak pernah digunakan untuk menceritakan profil sebuah keluarga.
Kalimat “ayahku adalah seorang tukang becak” atau “ayahku bekerja sebagai pemulung”
tidak pernah muncul dalam BSE.
Bagian keempat atau bagian terakhir buku ini membahas
mengenai isu-isu seputar pembangunan karakter. Isu pembangunan karakter memang
sempat hangat diperbincangkan, apalagi ketika pemerintah mencanangkan gerakan
revolusi mental. Pembahasan mengenai isu-isu pembentukan karakter hingga saat
ini kurasa masih sangat relevan dan akan terus relevan mengingat mental para
pemuda kita masih amburadul. Ini terbukti dengan berbagai berita tentang
kelakuan para remaja kita.
Buku ini diterbitkan tahun 2019 sehingga saat ini usianya kurang lebih mencapai lima tahun. Awalnya kukira buku ini akan membahas hal-hal mengenai kebijakan-kebijakan di era kurikulum merdeka. Tapi setelah tahu tahun terbitnya, tentu tak mungkin ada pembahasan mengenai kurikulum merdeka. Meskipun demikian buku ini perlu dibaca oleh kalangan pendidik maupun orang tua. Di beberapa artikel buku ini menyuguhkan cara pandang baru dalam melihat persoalan pendidikan. Namun, terkadang di artikel lain, pandangan-pandangan yang disajikan terkait pendidikan adalah pandangan yang sudah umum. Penulis hanya memperkuatnya dengan teori-teori, data-data, hingga pengalamannya sendiri. Penulis mencoba mengurai permasalahan-permasalahan pendidikan agar lebih mudah dilihat. Ya, memang begitulah. Di bagian sampul belakang memang tertulis demikian dan sekaligus menawarkan solusi alternatif yang bisa kita menfaatkan untuk kebaikan pendidikan pada masa yang akan datang. Meski yang disebut solusi alternatif bagiku tidak terlalu tampak di dalamnya. Mungkin aku saja yang kurang teliti membaca. Mungkin.
Informasi Buku:
Judul: Nalar Kritis Pendidikan
Penulis: Dr. M. Arfan Mu'ammar, M.Pd.I
Penerbit: Ircisod
Tahun Terbit: 2019
Halaman: 243 hlm.
Kategori: Esai
Kelas: Pendidikan
ISBN: 978-623-7378-03-7
---------------------------------
Komentar
Posting Komentar
Silakan tinggalkan komentar Anda!